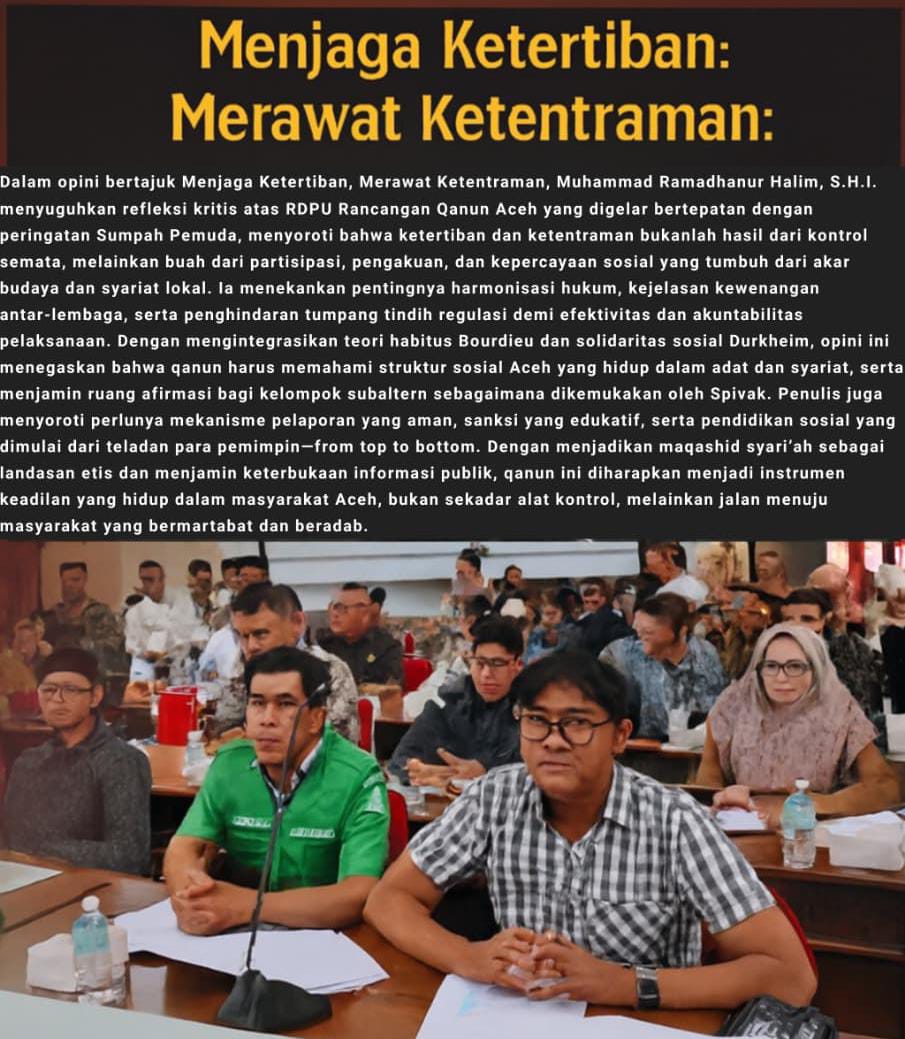Ditulis/disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.i.,
Indonesiainvestigasi.com
RAPAT Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan di aula serba-guna DPRA pada hari selasa 28 Oktober 2025 bersamaan dengan peringatan semangat hari Sumpah Pemuda menjadi panggung penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menakar arah regulasi yang akan berdampak langsung pada kehidupan sosial Aceh. Qanun ini bukan sekadar produk hukum, melainkan cerminan nilai, pengalaman dan harapan kolektif masyarakat Aceh.
Ketertiban dan ketentraman bukanlah hasil dari kontrol semata, melainkan buah dari kepercayaan, pengakuan dan partisipasi. Oleh karena itu, rancangan qanun ini harus dibangun di atas fondasi yang kokoh: hukum yang adil, struktur sosial yang mudah dipahami dan nilai syariat yang dijaga secara konsisten.
Aspek yuridis menjadi titik awal yang tak bisa diabaikan. Qanun ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta qanun sektoral lainnya. Harmonisasi vertikal dan horizontal sangat penting agar tidak terjadinya konflik norma yang berujung pada revisi dini setelah regulasi ini diterbitkan.
Lebih jauh, qanun ini harus dipastikan tidak berpotensi terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lainnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA), Komisi Informasi Aceh (KIA), Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan/atau lembaga pengawasan lainnya. Ketertiban publik yang menyangkut informasi, penyiaran dan ekspresi warga harus dikoordinasikan secara baik agar terhindar adanya duplikasi atau konflik kewenangan.
Tumpang tindih regulasi ini tidak hanya melemahkan efektivitas dalam pelaksanaannya, tetapi juga menimbulkan kebingungan hukum di lapangan. Oleh karena itu, RDPU harus menjadi ruang untuk memetakan secara jelas batas-batas kewenangan antar lintas setiap instansi yang ada dan memastikan bahwa qanun ini tidak melampaui atau mengulang fungsi lembaga lain.
Aspek sosiologis dan kultural juga harus menjadi jantung dari hasil RDPU ini. Ketertiban dan ketentraman tidak bisa dipaksakan dari atas, melainkan tumbuh dari kebiasaan, nilai dan solidaritas lokal. Teori habitus dari Bourdieu memberi kita pemahaman bahwa, perilaku masyarakat Aceh dibentuk oleh struktur sosial yang telah lama hidup secara adat, syariat dan pengalaman kolektif.
Qanun yang tidak memahami habitus ini akan gagal diterapkan atau bahkan menimbulkan resistensi. Ketentraman masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kohesi komunitas. Solidaritas sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, mengenai fondasi ketahanan sosial. Qanun harus memperkuat ikatan ini, bukan meretakkannya dengan pendekatan yang terlalu represif.
Dalam konteks Aceh, ketertiban bukan hanya soal larangan, tetapi juga soal pengakuan terhadap keberagaman adat, ekspresi budaya dan peran komunitas lokal. Hasil dari berbagai pemaparan, tanggapan, usulan dan perbaikan yang disampaikan dalam RDPU harus digali secara mendalam agar qanun menjadi cerminan dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh, bukan sebagai bayangan asing yang dipaksakan demi lahirnya aturan perundang-undangan yang jauh dari subtansi dan kebutuhan.
Aspek partisipatif menjadi penentu legitimasi sosial qanun. Hasil RDPU yang diharapkan oleh semua stakeholder yang berhadir haruslah inklusif karena telah melibatkan tokoh adat, ulama, perempuan, pemuda dan kelompok rentan lainnya. Tanpa partisipasi dan masukkan yang bermakna ini, qanun akan kehilangan daya hidupnya.
Subaltern, sebagaimana dikemukakan oleh Spivak, mereka yang selama ini tidak punya suara dalam wacana dominan. Qanun ini harus menjadi ruang afirmasi bagi mereka, bukan sekadar pengulangan struktur kekuasaan lama.
Aspek administratif dan kelembagaan juga tak kalah penting. Qanun ini nantinya harus menetapkan struktur pelaksanaan yang jelas, sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme evaluasi bersifat partisipatif. Tanpa ini, pelaksanaan akan berjalan pincang dan tidak akuntabel.
Sanksi dalam qanun harus proporsional dan edukatif. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat intimidasi, tetapi harus menjadi sarana pembelajaran sosial. Etika penegakan harus dijaga agar tidak menimbulkan stigma atau ketakutan.
Tujuan sosial dari qanun ini harus dirumuskan secara eksplisit. Apakah untuk mencegah konflik, membangun solidaritas, atau memperkuat perlindungan sosial? Indikator keberhasilan harus disusun agar evaluasi tidak bersifat subjektif.
Qanun juga harus adaptif terhadap perubahan sosial. Dinamika media sosial, urbanisasi dan migrasi harus diantisipasi. Ketertiban tidak bisa dibatasi pada ruang fisik saja, tetapi juga harus merambah ruang digital dan simbolik.
Nilai maqashid syari’ah harus menjadi landasan etis qanun. Perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, harta dan lingkungan harus tercermin secara zhahir (terang dan jelas) dalam setiap pasal. Ini bukan hanya soal syariat, tetapi soal kemanusiaan yang universal.
Konsistensi dan komitmen terhadap syari’at Islam harus dijaga secara utuh. Jangan sampai ada pasal yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap nilai-nilai syari’at. Hasil dari RDPU harus menjadi ruang klarifikasi dan penyelarasan agar qanun tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu.
Hasil RDPU terhadap qanun ini juga harus memperjelas mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses. Warga harus tahu bagaimana menyampaikan aspirasi atau melaporkan pelanggaran tanpa takut atau terhambat secara birokrasi.
Qanun harus mendorong penyelesaian konflik secara damai dan restoratif. Musyawarah, mediasi adat dan pendekatan komunitas harus diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum lokal (local wisdom).
Pendidikan sosial dan budaya harus menjadi bagian dari implementasi qanun. Ketertiban dan ketentraman tidak bisa dibentuk hanya dengan adanya sanksi, tetapi harus ditanamkan melalui pendidikan dan keteladanan secara menyeluruh “thoroughly/comprehensively” diawali dari para pimpinan/pejabat sebagai uswatun hasanah “From top to bottom”
Peran media lokal dan tokoh masyarakat sangat penting dalam sosialisasi qanun. Mereka bukan hanya menjadi jembatan antara regulasi dan realitas semata. Namun dari hasil RDPU tersebut juga harus mampu melibatkan mereka secara aktif serta ekspresif mengawal implementasinya.
Qanun juga harus mempertimbangkan aspek gender dan inklusi sosial. Perempuan, anak dan penyandang disabilitas harus dilindungi secara eksplisit, bukan hanya disebut secara umum di dalamnya.
Keterbukaan informasi publik tentang qanun harus dijamin. Draft, proses RDPU dan hasil akhir harus dapat diakses oleh masyarakat secara luas agar tercipta akuntabilitas.
Pada kesimpulannya, hasil dari RDPU bukan hanya ruang konsultasi, tetapi arena pembentukan makna sosial. Ia adalah proses pembelajaran kolektif, di mana masyarakat dan pemerintah saling mendengar dan membentuk arah kebijakan secara bersama-sama.
Jika semua aspek ini dikaji dan diintegrasikan secara utuh, maka qanun yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosial, kekuatan hukum dan daya transformasi yang nyata. Ia tidak hanya akan berjalan, tetapi akan hidup dalam masyarakat Aceh yang berkarakter.
Semoga instansi yang berwenang dapat menjalankan tugasnya tersebut sebagai sebagai sebuah amanah, sehingga menjadikan qanun ini sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kontrol. Ketertiban dan ketentraman bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju masyarakat yang bermartabat dan beradab.
-M12H-