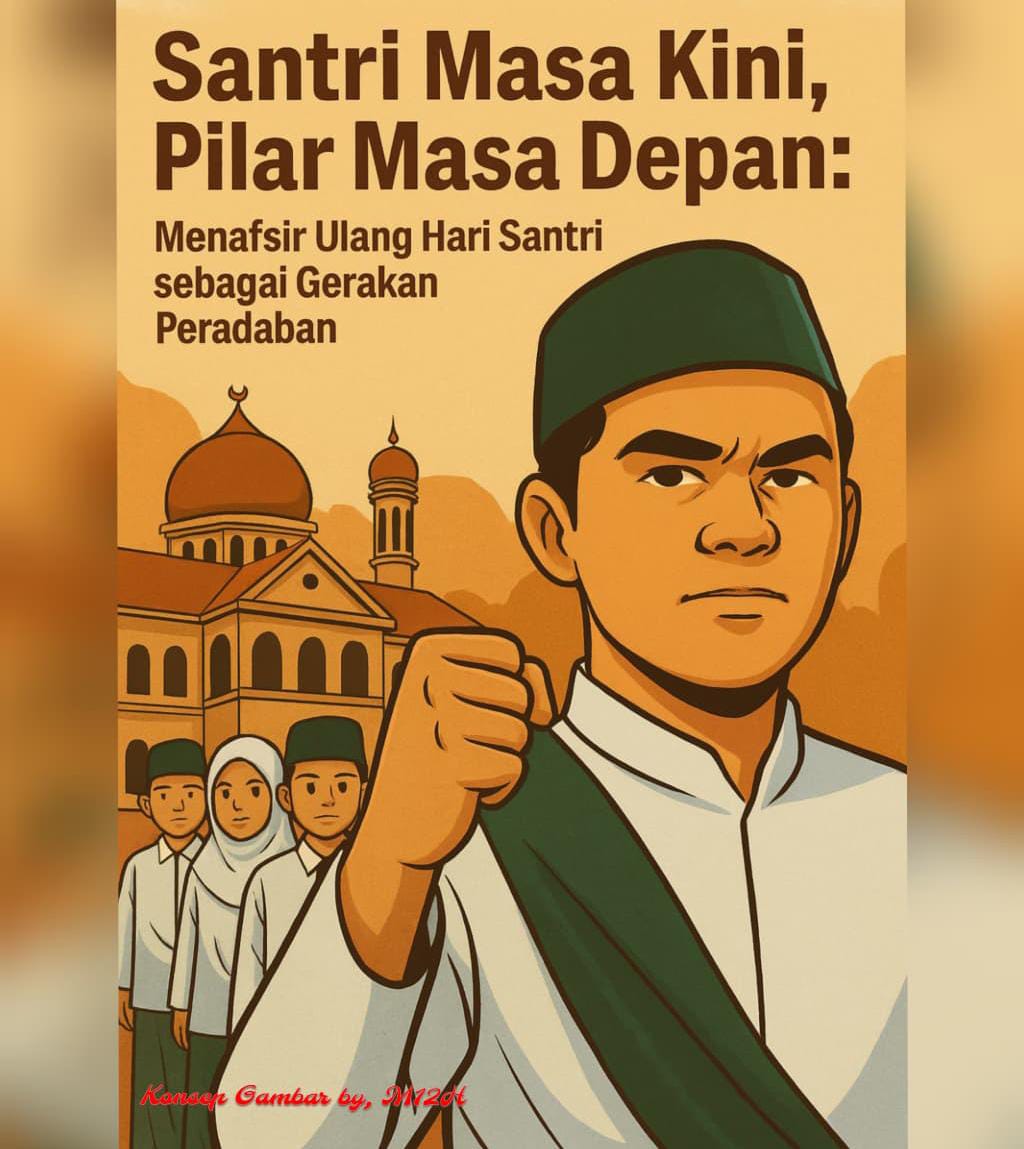Ditulis/disusun oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,
(Alumni Dayah Butanul Ulum Langsa – Alumni Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh – Juga Pengajar/guru di Dayah Lampoh Beut Aceh Besar – Kader ANSOR Provinsi Aceh)
Indonesiainvestigasi.com
HARI Santri bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah sebuah refleksi secara kolektif tentang peran santri dalam sejarah dan masa depan bangsa. Sejak ditetapkannya pada tanggal 22 Oktober 2015 yang lalu. Hari Santri telah menjadi ruang simbolik untuk mengakui kontribusi nyata para kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun peradaban di nusantara.
Momentum ini berakar dari “Resolusi Jihad” yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Seruan itu bukan hanya panggilan perang, tetapi juga manifestasi keberanian spiritual yang melampaui batas-batas pesantren. Santri tampil sebagai penjaga akidah sekaligus pembela tanah air, hingga lahirlah sebuah syair berjudul “Ya Lal Wathan”
Namun, tantangan hari ini berbeda. Generasi santri masa kini hidup dalam lanskap digital, geopolitik dan sosial yang jauh lebih kompleks. Maka, makna Hari Santri harus ditafsir ulang sebagai gerakan peradaban, bukan hanya sekadar nostalgia sejarah masa lalu.
Santri masa depan perlu mengembangkan spiritualitas yang aktif dan kontributif. Mereka tidak cukup hanya menjaga ritual, tetapi juga harus mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam praksis sosial yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Keilmuan santri juga harus berdaya saing. Kitab kuning tetap menjadi fondasi, tetapi harus berdialog dengan ilmu kontemporer: dari filsafat hingga kecerdasan buatan. Santri yang mampu menjembatani tradisi dan inovasi akan menjadi pemimpin intelektual masa depan.
Dalam konteks Aceh, peran santri memiliki dimensi historis dan kultural yang khas. Pesantren atau dayah bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat dokumentasi sejarah, penjaga adat dan ruang transformasi sosial. Maka, penguatan kapasitas santri Aceh harus berbasis lokal namun berpandangan global.
Santri juga harus menjadi penjaga NKRI yang cerdas. Bukan hanya melawan radikalisme, tetapi juga melawan disinformasi, korupsi dan ketidakadilan. Mereka harus tampil sebagai benteng moral yang mampu merawat demokrasi dalam bingkai keberagaman.
Inovasi berbasis tradisi adalah kunci. Santri harus mampu mengembangkan teknologi, seni dan ekonomi kreatif yang berakar dari nilai-nilai pesantren. Digitalisasi kitab kuning, platform dakwah interaktif serta dokumentasi sejarah pesantren adalah contoh yang konkret.
Kepemimpinan santri masa depan harus etis dan kolaboratif. Mereka tidak cukup menjadi pemimpin komunitas, tetapi harus mampu memimpin lintas sektor: pendidikan, hukum, ekonomi dan budaya. Kepemimpinan yang berakar pada akhlak akan menjadi penyeimbang dunia yang semakin pragmatis.
Hari Santri juga harus menjadi ruang refleksi tentang identitas digital santri. Di era media sosial, santri harus menjadi model komunikasi yang santun, etis dan edukatif. Mereka harus mampu membangun narasi Islam yang ramah, cerdas dan membebaskan.
Pendidikan pesantren harus bertransformasi. Kurikulum harus mengintegrasikan literasi digital, kewirausahaan dan pemikiran kritis tanpa kehilangan ruh keilmuan klasik. Santri yang memahami teknologi dan tetap teguh pada nilai akan menjadi agen perubahan.
Santri juga harus menjadi pelopor dokumentasi sejarah. Di Aceh, misalnya, dokumentasi keluarga, pesantren dan perjuangan lokal harus diarsipkan secara digital dan visual. Ini bukan sekadar pelestarian, tetapi juga strategi membangun identitas dan kebanggaan kolektif.
Hari Santri harus menjadi gerakan literasi. Santri harus menulis, membaca, dan berdialog. Mereka harus mengisi ruang publik dengan gagasan, bukan hanya dengan ceramah. Literasi adalah senjata utama dalam membangun peradaban.
Santri juga harus menjadi pelopor keamanan digital. Di tengah ancaman siber, mereka harus memahami etika digital, privasi, dan keamanan informasi. Santri yang sadar digital akan menjadi penjaga moralitas dunia maya.
Gerakan santri masa depan harus berbasis komunitas. Mereka harus membangun ekosistem pendidikan, ekonomi, dan budaya yang saling menopang. Kolaborasi antar pesantren, kampus dan komunitas lokal akan memperkuat daya tahan sosial.
Hari Santri juga harus menjadi ruang ekspresi seni dan budaya. Santri harus mampu mengemas nilai-nilai Islam dalam bentuk seni visual, musik dan narasi kreatif. Ini adalah strategi dakwah yang lebih humanis dan komunikatif.
Santri masa depan harus menjadi diplomat budaya. Mereka harus mampu menjelaskan Islam Indonesia kepada dunia dengan bahasa yang ramah, cerdas dan kontekstual. Diplomasi santri adalah diplomasi peradaban.
Hari Santri bukan hanya milik pesantren, tetapi milik bangsa. Maka, gerakan ini harus melibatkan semua elemen: pemerintah, akademisi, seniman dan masyarakat sipil. Sinergi ini akan memperkuat posisi santri sebagai pilar masa depan.
Di Aceh, Hari Santri bisa menjadi momentum konsolidasi antara tradisi syariah, pendidikan pesantren dan reformasi kelembagaan. Santri Aceh harus tampil sebagai pemikir, pelaku dan penjaga nilai dalam proses transformasi sosial.
Pada kesimpulannya, Hari Santri harus menjadi ruang kontemplasi dan aksi. Ia bukan sekadar seremoni, tetapi gerakan panjang menuju peradaban yang adil, beradab dan berkelanjutan. Santri masa kini adalah pilar masa depan.
-M12H-