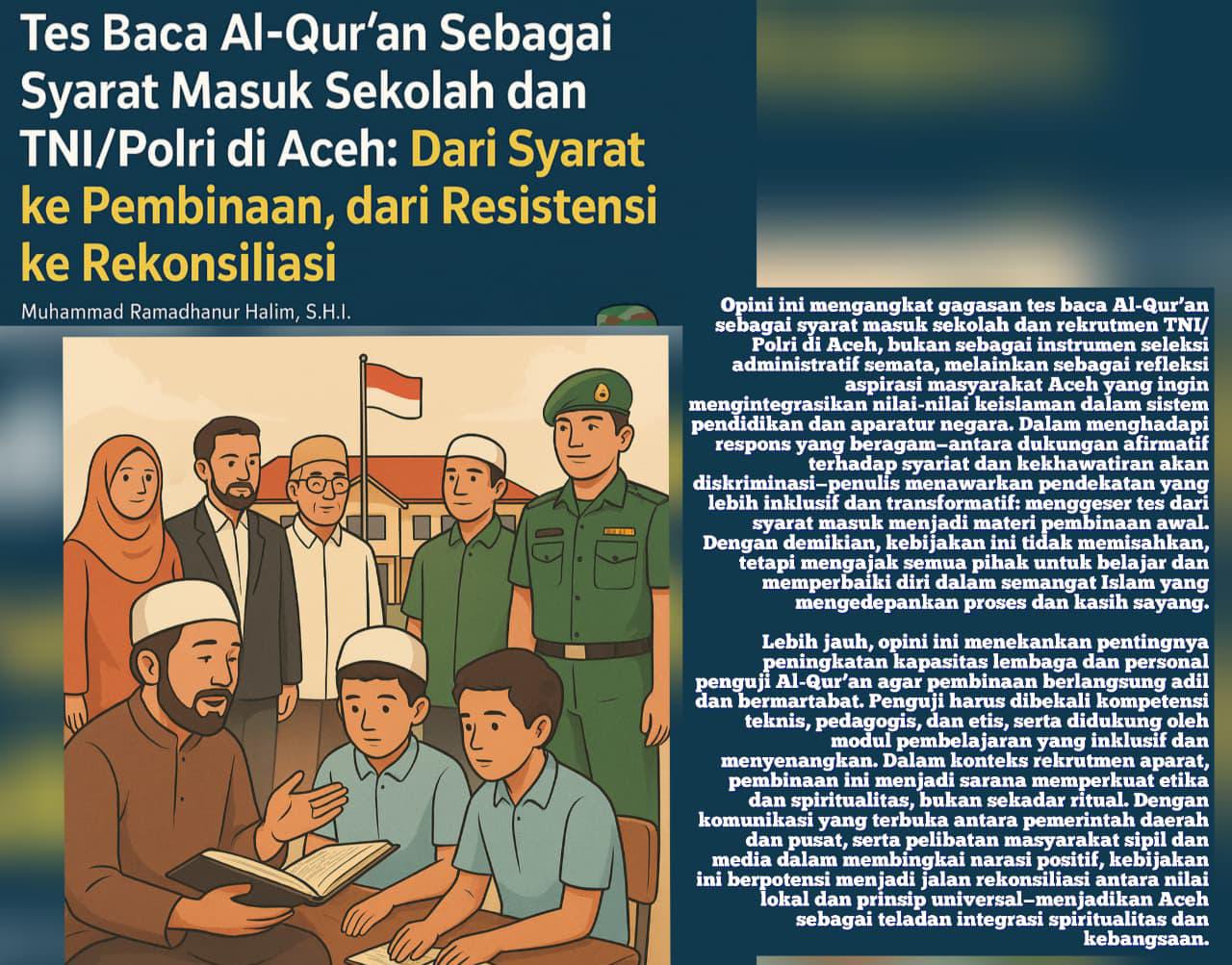Disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H,I.,
Indonesiainvestigasi.com
GAGASAN menjadikan tes baca Al-Qur’an sebagai syarat masuk sekolah dan rekrutmen TNI/Polri di Aceh, sebagaimana diusulkan oleh Muzakir Manaf (Mualem) selaku Gubernur Aceh, diharapkan bukan hanya sekadar wacana dalam bentuk administratif. Namun, merupakan refleksi dari aspirasi masyarakat Aceh yang ingin melihat nilai-nilai keislaman lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan dan aparatur negara. Akan tetapi, seperti halnya gagasan yang menyentuh pada ranah identitas dan kebijakan publik, respons terhadapnya tidaklah seragam. Sebagian menyambutnya sebagai langkah afirmatif terhadap syari’at Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai potensi lahirnya diskriminasi dan eksklusi sosial.
Untuk menjembatani perbedaan ini, pendekatan yang digunakan harus lebih dari sekadar legal-formal. Ia harus menyentuh aspek psikologis, sosial dan pedagogis dari masyarakat Aceh yang plural dalam praktik dan pemahaman keagamaannya. Tes baca Al-Qur’an tidak boleh dimaknai sebagai alat seleksi yang menyingkirkan, melainkan sebagai sarana pembinaan yang mengajak. Dengan demikian, resistensi yang bermunculan kemudian bukan untuk dilawan, tetapi dipahami dan dijawab dengan pendekatan yang lebih inklusif.
Pihak yang kontra terhadap gagasan ini umumnya berangkat dari kekhawatiran mereka akan eksklusivitas kebijakan. Mereka mempertanyakan bagaimana nasib anak-anak Aceh yang belum lancar membaca Al-Qur’an, atau bagaimana posisi warga non-Muslim dalam sistem pendidikan dan rekrutmen nasional. Kekhawatiran ini sah dan perlu dijawab dengan jaminan bahwa, kebijakan tersebut tidak akan menjadi alat pemisah, melainkan jembatan pembinaan spiritual yang terbuka bagi semua.
Salah satu cara untuk mengubah persepsi kontra menjadi pro adalah dengan menggeser posisi tes dari “syarat masuk” menjadi “materi pembinaan awal.” Artinya, tes baca Al-Qur’an dilakukan setelah peserta diterima, sebagai bagian dari orientasi nilai dan pembinaan karakter. Dengan pendekatan ini, tidak ada yang ditolak karena belum bisa, tetapi semua diajak untuk belajar dan memperbaiki diri. Ini sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan proses, bukan hanya hasil.
Bagi pihak yang pro, pendekatan pembinaan justru memperkuat nilai yang mereka perjuangkan. Tes baca Al-Qur’an bukan lagi sekadar ritual formalitas, tetapi menjadi simbol komitmen terhadap nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab dan kasih sayang. Dengan menjadikannya bagian dari proses pembinaan, nilai-nilai Al-Qur’an bisa diinternalisasi secara lebih mendalam dan kontekstual.
Namun, agar pendekatan ini berhasil, perlu adanya pembenahan serius terhadap lembaga dan personal yang bertugas menguji bacaan Al-Qur’an. Saat ini, belum semua institusi memiliki standar yang seragam dalam hal pengujian. Ada yang terlalu teknis, ada yang terlalu longgar dan ada pula yang kurang sensitif terhadap latar belakang peserta. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penguji baca Al-Qur’an saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.
Penguji baca Al-Qur’an harus memiliki kompetensi yang tidak hanya secara teknis, tetapi juga pedagogis dan etis. Mereka harus mampu membimbing, bukan menghakimi. Mereka harus memahami bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an bukan hanya soal tajwid dan makhraj, tetapi juga soal proses belajar yang dipengaruhi oleh latar sosial, pendidikan dan psikologis peserta.
Untuk itu, pelatihan metodologi pengajaran Al-Qur’an harus menjadi bagian dari kurikulum penguji. Mereka perlu dibekali dengan pendekatan yang humanis, kontekstual dan berbasis pada nilai. Bahkan, pembentukan lembaga sertifikasi penguji di bawah otoritas yang kredibel seperti MPU atau Dinas Syariat Islam bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kualitas dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Selain itu, perlu ada modul pembinaan baca Al-Qur’an yang dirancang secara inklusif. Modul ini harus bisa diakses oleh semua peserta, baik yang sudah lancar maupun yang masih belajar. Formatnya bisa berupa kelas intensif, mentor sebaya, atau platform digital yang interaktif. Tujuannya adalah menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan membina.
Dalam konteks rekrutmen TNI/Polri, pendekatan ini juga bisa memperkuat etika dan spiritualitas para aparat. Tes baca Al-Qur’an bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, amanah dan tanggung jawab. Dengan pembinaan yang tepat, aparat bisa menjadi representasi nilai-nilai luhur yang diharapkan oleh masyarakat Aceh.
Namun, agar kebijakan ini tidak menimbulkan resistensi di tingkat nasional, perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Aceh harus mampu menjelaskan bahwa, kebijakan ini bukan bentuk pemisahan, tetapi merupakan bentuk penguatan nilai lokal dalam kerangka kebangsaan. Dengan komunikasi yang terbuka dan argumentasi yang kuat, resistensi bisa diubah menjadi dukungan.
Di sisi lain, masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Tokoh agama, pendidik, aktivis dan komunitas lintas agama harus diajak berdialog secara bersama untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan polarisasi sosial. Dialog ini penting untuk membangun legitimasi sosial dan memperkuat dukungan publik.
Media juga memiliki peran penting dalam membingkai narasi kebijakan ini. Alih-alih menyoroti adanya potensi diskriminasi, media harus bisa mengangkat kisah-kisah inspiratif dari peserta yang berhasil belajar membaca Al-Qur’an melalui program pembinaan. Narasi positif ini bisa mengubah persepsi publik dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan.
Pendidikan formal juga harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini. Sekolah-sekolah di Aceh bisa mulai mengintegrasikan pembinaan baca Al-Qur’an dalam kurikulum pendidikan karakter. Dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, kemampuan baca Al-Qur’an bisa menjadi bagian dari proses pembentukan pribadi yang utuh.
Lebih jauh, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk merevitalisasi pendidikan Al-Qur’an di Aceh. Banyak lembaga pendidikan Islam yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah bisa membangun ekosistem pendidikan Al-Qur’an yang terintegrasi dan berkualitas.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengintegrasikan nilai lokal dalam sistem pendidikan dan rekrutmen. Aceh bisa menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keislaman bisa diimplementasikan secara inklusif, edukatif dan transformatif tanpa menimbulkan eksklusi sosial.
Namun, semua ini hanya bisa tercapai jika kebijakan dijalankan dengan niat yang tulus dan pendekatan yang bijak. Jika dijadikan alat politik atau simbol identitas semata, maka resistensi akan semakin menguat. Sebaliknya, jika dijalankan sebagai proses pembinaan nilai, maka kebijakan ini bisa menjadi jalan rekonsiliasi antara nilai lokal dan prinsip universal.
Kesimpulannya adalah, tes baca Al-Qur’an bukanlah soal siapa yang sudah bisa, tetapi soal siapa yang bersedia belajar. Ia bukan soal seleksi, tetapi soal pembinaan. Ia bukan soal pemisahan, tetapi soal penyatuan nilai. Dan dalam semangat Islam yang “rahmatan lil ‘alamin,” semua proses pembinaan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, keadilan dan kebijaksanaan.
Aceh, dengan sejarah panjangnya dalam mengintegrasikan agama dan negara, memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa, spiritualitas dan kebangsaan bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sayap yang bisa membawa masyarakat terbang lebih tinggi menuju keadaban. Jika dijalankan dengan bijak, kebijakan ini bisa menjadi warisan nilai yang membanggakan, bukan hanya sekadar wacana.
-M12H-