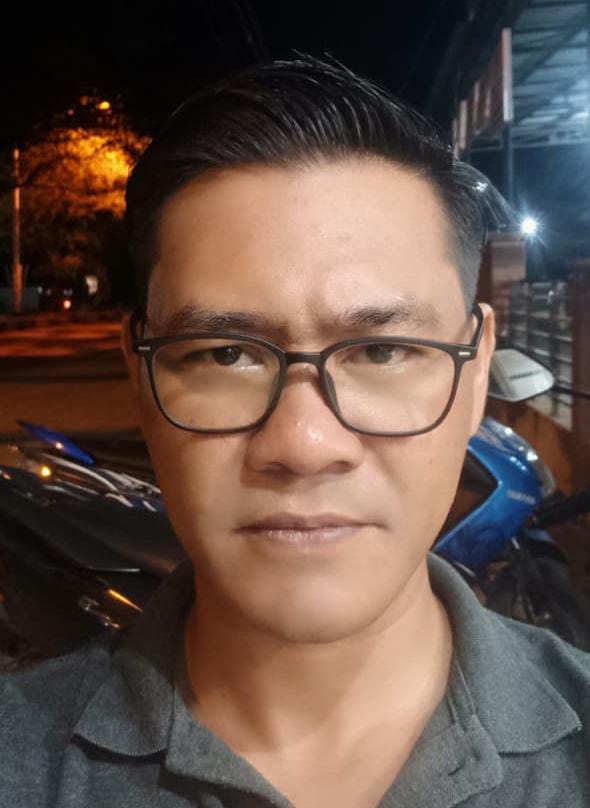Disusun oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,
Indonesiainvestigasi.com
PERISTIWA Gerakan 30 September 1965 bukan sekadar catatan sejarah berdarah, melainkan simpul kompleks dari ideologi, kekuasaan, dan kemanusiaan yang terurai dalam tragedi nasional. Di balik narasi resmi yang selama puluhan tahun dikukuhkan oleh negara, tersimpan lapisan-lapisan realitas yang menuntut pembacaan ulang secara jujur dan reflektif. Generasi muda hari ini, yang tumbuh dalam era keterbukaan informasi, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mengingat, tetapi juga memahami secara kritis.
G30S/PKI sering kali dikenang sebagai malam kelam ketika tujuh perwira tinggi TNI AD dibunuh secara brutal dan jasad mereka dibuang ke Lubang Buaya. Narasi ini, yang dikukuhkan melalui film propaganda dan kurikulum sekolah, menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang tunggal. Namun, sejarah bukanlah monolit. Ia adalah ruang tafsir yang harus dibuka dengan keberanian intelektual dan empati kemanusiaan.
Pasca peristiwa tersebut, Indonesia memasuki fase pembantaian massal yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ratusan ribu orang dibunuh, ditahan tanpa proses hukum, atau diasingkan karena tuduhan keterlibatan dengan PKI. Banyak di antaranya adalah petani, guru, seniman, bahkan anak-anak. Kekerasan ini bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik yang melumpuhkan hak untuk bicara, berpikir, dan berbeda.
Generasi muda perlu memahami bahwa tragedi ini bukan hanya soal ideologi komunis versus militerisme, tetapi tentang bagaimana negara dan masyarakat bisa terjebak dalam logika kekerasan kolektif. Ketika rasa takut dikapitalisasi, dan perbedaan dianggap ancaman, maka kemanusiaan menjadi korban pertama. Ini adalah pelajaran penting dalam membangun demokrasi yang sehat.
Literasi sejarah yang kritis menjadi kunci. Anak muda harus berani menggali sumber alternatif, membaca kesaksian korban, dan memahami konteks global saat itu, termasuk peran negara asing dalam mendukung operasi antikomunis. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi pewaris narasi, tetapi juga penafsir aktif sejarah bangsanya.
Penting pula untuk menyadari bahwa luka sejarah tidak bisa disembuhkan dengan penghapusan atau penyangkalan. Ia harus diakui, didengar, dan dijadikan bahan pembelajaran. Rekonsiliasi bukan berarti melupakan, tetapi menyusun ulang makna agar tidak terulang. Dalam konteks Aceh, yang juga memiliki sejarah panjang konflik dan rekonsiliasi, pendekatan ini sangat relevan.
Sebagai pendidik dan advokat etika, kita bisa mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam modul pendidikan yang interaktif dan kontekstual. Misalnya, melalui diskusi tematik, simulasi rekonsiliasi, atau karya seni yang menggambarkan sisi kemanusiaan dari tragedi tersebut. Ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter.
Nilai-nilai profetik seperti keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan kepada yang tertindas harus menjadi landasan dalam membaca sejarah. Al-Qur’an mengajarkan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan bahwa setiap jiwa memiliki hak untuk dihormati. Dalam konteks G30S/PKI, kita belajar bahwa fitnah ideologis bisa melahirkan pembunuhan massal jika tidak dikendalikan oleh etika.
Kita juga perlu mengkritisi bagaimana kekuasaan membentuk narasi. Siapa yang berhak bicara? Siapa yang dibungkam? Dalam sejarah G30S/PKI, suara korban dan keluarga mereka lama terpinggirkan. Kini, saat ruang publik lebih terbuka, kita harus memberi tempat bagi narasi alternatif yang lebih manusiawi dan adil.
Generasi muda harus diajak untuk tidak terjebak dalam glorifikasi kekerasan. Film, buku, dan media sosial harus dijadikan alat edukasi, bukan propaganda. Kita bisa mendorong produksi konten sejarah yang berbasis riset, empati, dan keberagaman perspektif. Ini adalah bagian dari jihad intelektual yang sangat mulia.
Dalam konteks pendidikan Aceh, pendekatan ini bisa diselaraskan dengan nilai-nilai lokal seperti hikayat, adat, dan semangat musyawarah. Sejarah bukan hanya milik Jakarta, tetapi juga milik kampung-kampung yang warganya ikut menjadi korban atau saksi. Kita perlu menggali narasi lokal agar sejarah menjadi lebih inklusif.
Kita juga harus mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh, tetapi juga melawan ketidakadilan dalam diri sendiri dan masyarakat. Mengakui kesalahan masa lalu adalah bentuk keberanian moral yang tinggi. Ini adalah fondasi bagi generasi yang ingin membangun masa depan yang lebih adil.
Pelajaran dari G30S/PKI bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Ia mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani belajar dari sejarahnya, bukan yang menutupinya. Generasi muda harus menjadi penjaga ingatan kolektif, bukan pengikut buta narasi dominan.
Pada kesimpulannya, mengenang G30S/PKI bukan untuk membuka luka, tetapi untuk menyulam makna. Dari darah dan air mata, kita bisa merajut pelajaran tentang kemanusiaan, keadilan, dan keberanian berpikir. Inilah warisan sejati yang harus kita jaga dan terus hidupkan dalam pendidikan, advokasi, dan kehidupan sehari-hari.
Nurhalim,