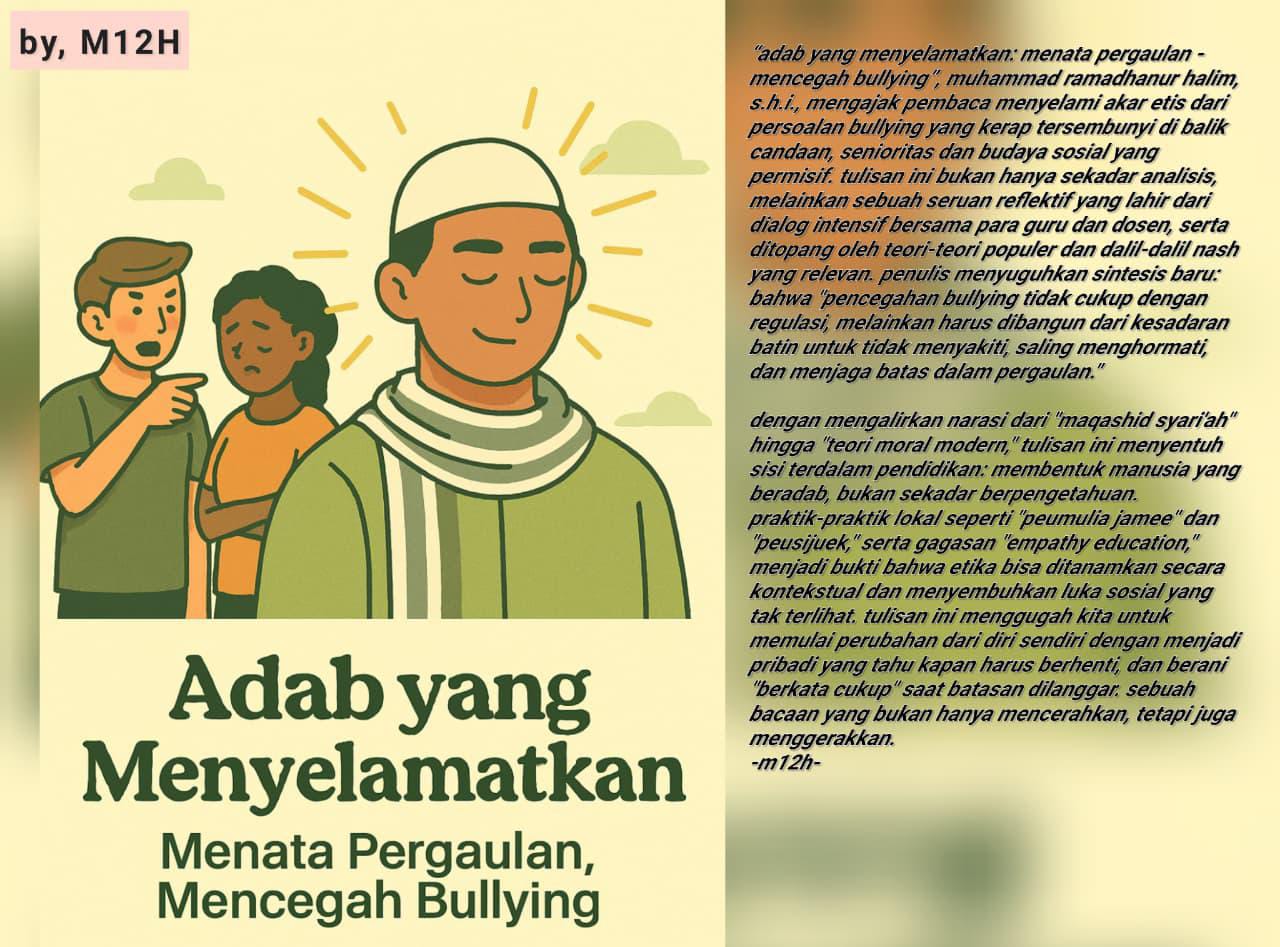Ditulis/disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,
Indonesiainvestigasi.com
DALAM ruang-ruang pendidikan, dari kelas dasar hingga perguruan tinggi, “fenomena bullying” masih menjadi luka yang terus menganga. Ia hadir dalam bentuk fisik, verbal, hingga psikologis ini seringkali tersembunyi di balik candaan, senioritas atau bahkan budaya institusional. Namun, dari berbagai diskusi dengan para guru, dosen dan pendidik, muncul satu benang merah: bahwa pencegahan bullying tidak cukup hanya dengan sanksi, tetapi harus ditopang oleh etika yang harus dipahami secara mendalam.
Etika, dalam pengertian ini, bukan hanya sekadar norma sosial, melainkan kesadaran batin untuk tidak menyakiti, untuk saling menghormati dan untuk menjaga batasan dalam pergaulan. Ia adalah fondasi moral yang menuntun manusia untuk memperlakukan sesama sebagai subjek yang utuh, bukan objek olok-olok atau dominasi.
Dalam Islam, prinsip ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan larangan menyakiti, baik secara langsung maupun dengan membiarkan kezaliman terjadi.
Al-Qur’an pun menegaskan larangan mencela dan merendahkan orang lain: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka…” (QS. Al-Hujurat: 11). Ayat ini bukan hanya melarang ejekan, tetapi juga mengajarkan “prinsip husnuzhan” dan penghargaan terhadap martabat manusia.
Dalam diskusi dengan para pendidik, muncul keprihatinan bahwa banyak tindakan bullying justru dibungkus dalam bentuk candaan. “Itu cuma bercanda,” sering menjadi tameng dari si pelaku. Padahal, dalam etika Islam, bercanda pun memiliki batasannya. Rasulullah saw bersabda, “Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa, celakalah dia, celakalah dia.” (HR. Abu Dawud). Bercanda yang menyakiti adalah bentuk kezaliman.
Teori psikologi sosial seperti “Social Dominance Theory” (Sidanius & Pratto, 1999) menjelaskan bahwa bullying sering muncul dari dorongan untuk mempertahankan hierarki sosial. Dalam konteks sekolah atau kampus, ini bisa muncul dalam bentuk senioritas, eksklusivitas kelompok atau adanya stereotip terhadap siswa tertentu.
Namun, teori “Moral Development” dari Lawrence Kohlberg memberi harapan. Ia menunjukkan bahwa manusia dapat berkembang dari moralitas yang berbasis hukuman ke moralitas berbasis prinsip universal. Artinya, pendidikan etika yang mendalam bisa menumbuhkan “kesadaran intrinsik” untuk tidak menyakiti dan menghormati sesama.
Dalam konteks lokal, para guru di Aceh menekankan pentingnya nilai “peumulia jamee” (memuliakan tamu) dan “peusijuek” (adat-istiadat dalam penyambutan atau syukuran) menjadi sebagai simbol penghormatan terhadap orang lain. Nilai-nilai ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan dan sejenisnya.
Dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi juga menyoroti pentingnya “empathy education”, yaitu pendidikan yang menumbuhkan kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Ini sejalan dengan konsep “ta’awun” (saling tolong-menolong) dalam Islam, yang menuntut kita untuk hadir sebagai penolong, bukan sebaliknya berperan sebagai penindas.
Dalam praktiknya, pencegahan bullying berbasis etika memerlukan tiga pilar:
(1) kesadaran untuk tidak menyakiti,
(2) penghormatan terhadap perbedaan, dan
(3) pengendalian diri dalam interaksi sosial. Ketiganya harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya lewat nasehat/tausyiah/ceramah, tetapi lewat keteladanan dan pembiasaan.
Pilar pertama, “tidak menyakiti,” adalah prinsip universal. Dalam Islam, ini dikenal sebagai “laa dharara wa laa dhiraar,” yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks pendidikan, ini berarti menciptakan ruang aman, baik secara fisik maupun emosional.
Pilar kedua, “respect,” atau penghormatan, menuntut kita untuk melihat orang lain sebagai pribadi yang utuh. Dalam teori “Recognition” dari Axel Honneth, penghormatan adalah syarat dasar bagi terbentuknya identitas yang sehat. Tanpa itu, individu rentan mengalami alienasi dan luka batin.
Pilar ketiga, “tidak berlebihan dalam pergaulan,” adalah bentuk pengendalian diri. Dalam Islam, ini disebut “i’tidal,” yaitu bersikap seimbang. Bercanda boleh, tetapi jangan sampai melukai. Dekat boleh, tetapi jangan melewati batas. Ini adalah seni menjaga relasi agar tetap sehat dan bermartabat.
Dari diskusi dengan para guru, muncul praktik-praktik baik seperti “lingkar refleksi,” di mana siswa diajak merenung bersama tentang perasaan mereka, atau “hari tanpa ejekan,” yang menjadi momentum untuk membangun empati. Praktik ini menunjukkan bahwa etika bisa ditanamkan lewat pengalaman, bukan hanya teori secara epistemik.
Para dosen juga menekankan pentingnya dibentuk sebuah kurikulum yang mengintegrasikan etika dalam semua mata pelajaran. Bukan hanya dalam pelajaran agama atau PPKn, tetapi juga dalam matematika, seni, bahkan olahraga. Karena etika bukan saja domain pada satu bidang studi, melainkan napas dari seluruh proses pendidikan.
Maka, pencegahan bullying bukan hanya soal regulasi atau hukuman. Ia adalah soal membangun budaya. Budaya yang menolak kekerasan, yang menghargai perbedaan dan yang menumbuhkan keberanian untuk berkata “cukup” ketika ada batasan yang dilanggar.
Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan menjaga kehormatan (hifzh al-‘ird) merupakan dua hal penting dari tujuan utama syari’at. Bullying merusak keduanya. Maka, mencegah bullying adalah bagian dari ibadah sosial, bagian dari menjaga amanah kemanusiaan.
Dari semua diskusi dan teori yang dihimpun, muncul satu sintesis penting: “bahwa etika bukan hanya alat pencegah, tetapi juga penyembuh”. Ia menyembuhkan luka batin, menyatukan yang tercerai, dan membangun ruang belajar yang penuh kasih dan keberanian.
Maka, mari kita mulai dari diri sendiri. Menjadi pribadi yang tidak menyakiti, saling menghormati dan yang memahami kapan harus berhenti. Karena dalam dunia yang sering bising dengan ejekan dan dominasi, kehadiran satu orang yang beretika akan menjadi cahaya yang menenangkan. Dan dari cahaya kecil itu tersebut akan menghadirkan perubahan besar yang berkelanjutan.
-M12H-