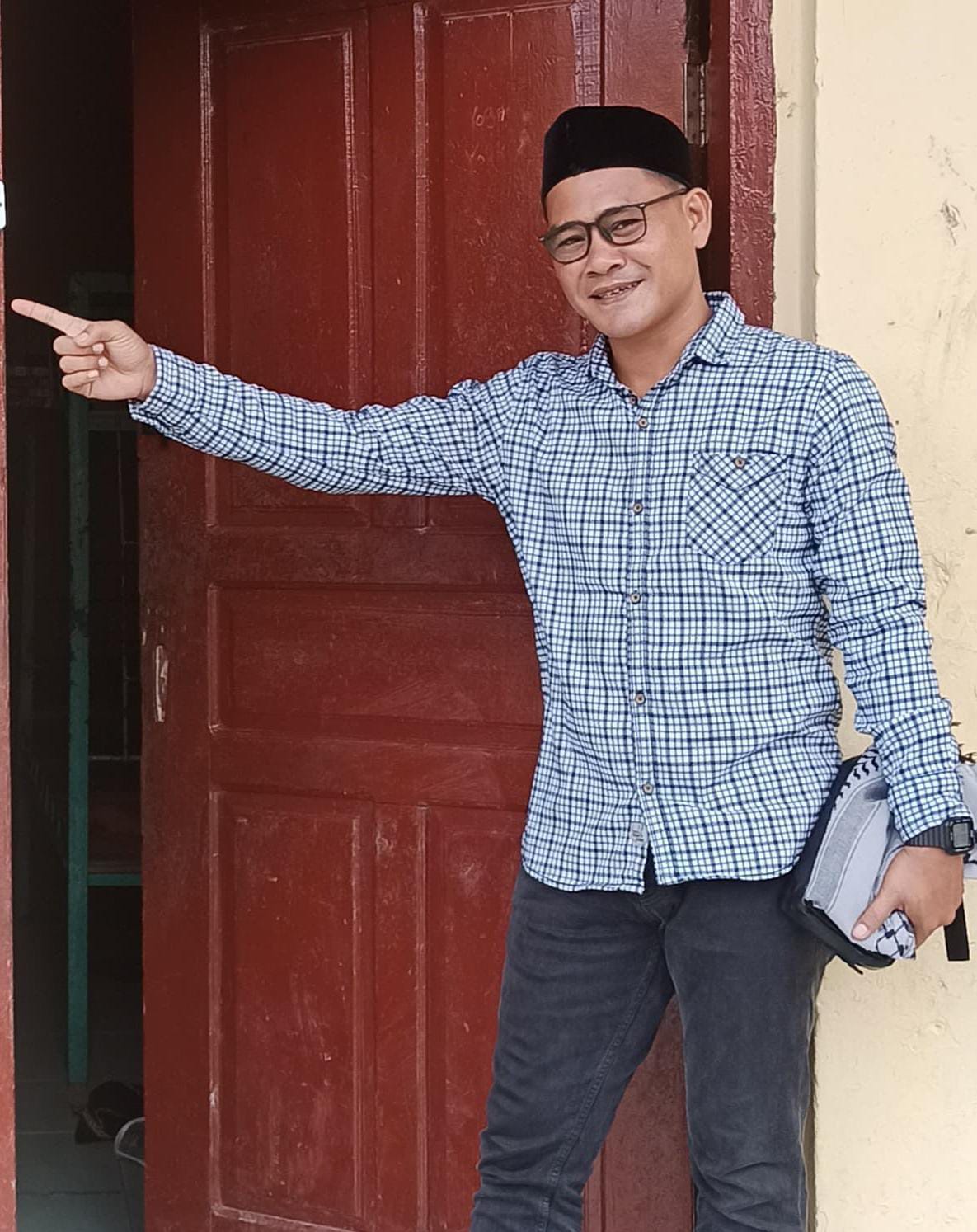Disusun oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,
Pemerhati/Pengamat
Indonesiainvestigasi.com
Zakat di Aceh memikul peran ganda—sebagai kewajiban spiritual dan mekanisme sosial untuk menciptakan keadilan ekonomi. Sebagai daerah bersyariat, pengelolaan zakat melalui institusi resmi seperti Baitul Mal bukan hanya soal tata kelola dana, tetapi cerminan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, harapan besar ini belum sejalan dengan capaian nyata.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan zakat di Aceh bersifat sistemik. Fragmentasi data mustahik, rendahnya partisipasi muzakki, serta lemahnya sinergi antar lembaga menjadikan distribusi zakat dirasa masih kurang tepat sasaran. Tak jarang pula birokrasi yang panjang dan perbedaan visi antar pemangku kepentingan menghambat gerak lembaga zakat dalam menjawab persoalan sosial yang dinamis.
Menuju periode 2025–2030, perubahan paradigma menjadi keharusan. Reformasi Baitul Mal harus menyentuh aspek kelembagaan, teknologi, dan peningkatan pendidikan serta kapasitas yang sering disebut dengan istilah SDM. Perubahan ini bukan sekadar kosmetik, melainkan transformasi substansial—mengganti cara lama yang lambat dan tertutup dengan sistem baru yang transparan, cepat, dan partisipatif.
Digitalisasi merupakan kunci pembuka era baru zakat. Mulai dari registrasi mustahik berbasis aplikasi, audit keuangan secara real-time, hingga pelaporan publik yang mudah diakses, teknologi harus dijadikan fondasi tata kelola zakat modern. Hal ini penting agar masyarakat dapat memantau dan percaya penuh pada proses dan hasil pengelolaan zakat.
Di sisi lain, kolaborasi antara Baitul Mal dan Lembaga Amil Zakat swasta mesti ditingkatkan. Dengan menyatukan data, jaringan, dan inovasi, zakat bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dalam waktu yang lebih singkat. Platform kolaboratif akan mengefisiensi kerja dan memperluas dampak sosial secara signifikan.
Penguatan pada sisi peningkatan pendidikan serta kapasitas dalam pengelolaan zakat juga merupakan prioritas mutlak yang menjadi proiritas kedepannya. Lembaga zakat membutuhkan figur-figur yang tidak hanya memahami aspek fiqh zakat, tetapi juga menguasai manajemen publik, sosial entrepreneurship, dan kebijakan berbasis maqashid syariah. Profesionalisme dan integritas adalah modal utama dalam menjalankan amanah ini.
Strategi zakat produktif patut dijadikan arah baru kebijakan. Alih-alih distribusi bantuan jangka pendek, zakat bisa diarahkan untuk membiayai usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan ini, zakat menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar subsidi.
Revisi terhadap Qanun Baitul Mal adalah langkah strategis yang tak terhindarkan. Peraturan perlu diselaraskan dengan tantangan zaman dan prinsip good governance. Akuntabilitas berbasis hasil dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan adalah elemen kunci yang akan memastikan zakat benar-benar berdampak.
Kesimpulannya adalah, zakat di Aceh perlu dipandang bukan sebagai simbol formalitas syariat, melainkan sebagai solusi konkrit dalam mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan akses ekonomi. Masa depan zakat ada di tangan sistem yang berani berubah, terbuka pada inovasi, dan berpihak pada keadilan.
Nurhalim,